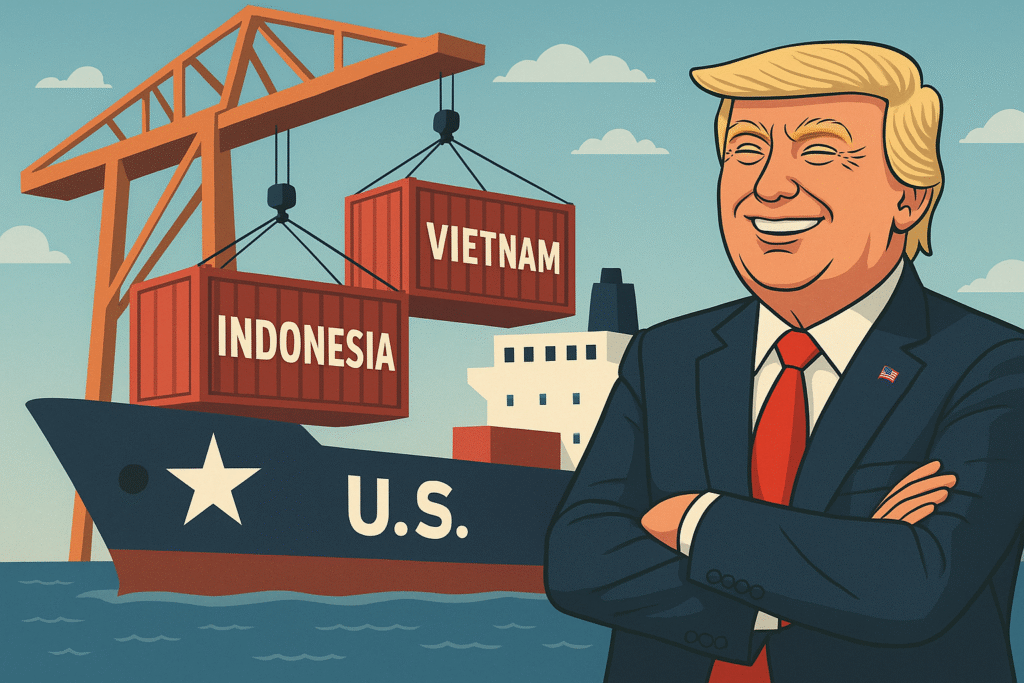Tarif 19 persen yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia, termasuk furnitur kayu, bukan sekadar kebijakan dagang. Ia adalah sinyal keras yang menguji daya tahan dan daya saing struktur industri nasional. Yang lebih mengkhawatirkan, tarif ini datang pada saat yang paling rentan ketika manufaktur Indonesia mulai kehilangan nafas di tengah tekanan biaya, volatilitas global, dan tantangan regulasi baru seperti EUDR dari Uni Eropa.
Vietnam, tetangga dekat kita di Asia Tenggara, menunjukkan arah yang berbeda. Negara itu memang turut dikenakan tarif 20 persen oleh AS pasca kebijakan Liberation Day Tariffs, tetapi posisi tawarnya tetap kuat. Mereka memiliki FTA aktif dengan Uni Eropa, tergabung dalam CPTPP dan RCEP, serta memiliki reputasi sebagai basis produksi bagi perusahaan-perusahaan global. Relokasi industri yang dahulu hanya ancaman kini menjadi kenyataan: satu per satu pabrik sepatu, tekstil, bahkan manufaktur kayu skala menengah mulai membuka lini produksi kedua di sana.
Tarif Tak Berdiri Sendiri
Masalahnya bukan pada angka 19 persen itu sendiri, melainkan dalam respons kita. Ketika negara lain menawarkan insentif fiskal, kawasan industri ekspor terpadu, dan pelayanan perizinan yang transparan, Indonesia sepertinya masih berkutat dengan logistik yang mahal, regulasi ekspor yang rumit, dan sistem insentif yang tambal sulam. Bahkan ketika satu per satu pelaku industri menjerit karena kehilangan margin ekspor, kebijakan nasional belum mampu menjawab cepat dan tepat.
Tarif AS bisa jadi mempercepat tren yang sebenarnya sudah mengakar yaitu deindustrialisasi dini yang terjadi di sektor-sektor padat karya dan berorientasi ekspor. Pemerintah memang memiliki program hilirisasi, tetapi tanpa daya saing biaya dan kemudahan berusaha, hilirisasi bisa menjadi proses yang sia-sia, di atas kertas iya, di lapangan belum tentu.
Ekspor Produk Kehutanan: Siapa yang Masih Bertahan?
Salah satu subsektor paling terdampak dari kebijakan tarif AS ini adalah produk kehutanan, khususnya furnitur kayu. Indonesia selama ini dikenal sebagai eksportir utama furnitur dari kayu tropis, dengan nilai ekspor ke AS yang mencapai lebih dari USD 1,5 miliar per tahun. Dari Jepara, Cirebon, hingga Pasuruan, ribuan pelaku industri kecil yang menggantungkan hidup pada permintaan pasar Amerika. Kini, dengan beban tarif 19 persen, daya saing mereka berpotensi terguncang, terutama karena sebagian besar belum memiliki sistem produksi efisien atau kemampuan untuk menanggung selisih harga.
Sementara itu, Vietnam yang juga mengekspor furnitur kayu dalam skala besar memiliki keunggulan struktural yang sulit ditandingi. Mereka memiliki zona industri terpadu, efisiensi logistik, serta dukungan kuat dari FTA aktif dengan berbagai negara. Walaupun kini dikenai tarif 20 persen oleh AS, produk Vietnam tetap lebih kompetitif karena skala produksi yang besar dan biaya yang rendah. Data perdagangan 2024 bahkan menunjukkan Vietnam sebagai eksportir furnitur kayu kamar tidur dan dapur terbesar ke AS, mengalahkan Tiongkok dan Malaysia. Jika tren ini berlanjut, maka risiko relokasi industri kehutanan dari Indonesia ke Vietnam bukan hanya kemungkinan tetapi keniscayaan.
Tidak Lebih Baik, Tetapi Lebih Siap
Mari kita bersikap adil, Vietnam bukan tanpa masalah. Upah buruh di beberapa wilayahnya kini mulai menanjak, dan tekanan terhadap lingkungan hidup pun meningkat. Namun keunggulan mereka terletak pada satu hal mendasar yaitu kejelasan strategi industri dan keberpihakan kepada ekspor.
Ketika tarif baru dari AS diumumkan, Vietnam dengan sigap menggelar negosiasi bilateral dan menawarkan insentif bagi pelaku industri yang berisiko relokasi keluar. Mereka tak tinggal diam. Di saat yang sama, Indonesia masih menunggu evaluasi lintas kementerian yang seringkali berlarut dan kurang sinkron. Padahal, Industri tidak menunggu.
Mencegah Relokasi, Memulihkan Daya Saing
Apa yang seharusnya dilakukan Indonesia?
- Pertama, menetapkan insentif fiskal khusus untuk industri terdampak tarif AS, dengan model yang terukur dan terfokus pada ekspor berkelanjutan.
- Kedua, mempercepat integrasi sistem logistik dan perizinan ekspor, khususnya untuk subsektor furnitur, alas kaki, dan tekstil.
- Ketiga, mengadopsi pendekatan proaktif dalam negosiasi dagang, dengan memastikan IEU-CEPA dan perjanjian lain segera diratifikasi dan dijalankan.
- Dan yang tak kalah penting, memastikan sistem traceability dan legalitas produk seperti yang diminta EUDR dapat diakses secara digital, murah, dan inklusif bagi UMKM.
Jangan Biarkan Industri Pergi Diam-Diam
Indonesia pernah menjadi raksasa manufaktur Asia Tenggara. Tapi perlahan, raksasa itu pincang karena keputusan yang tertunda, regulasi yang lambat, dan kebijakan yang tidak berpihak pada pelaku riil. Jika kita tidak bergerak cepat, industri tidak akan mati. Ia hanya akan berpindah. Dan ketika itu terjadi, ia tak akan mudah kembali.
Vietnam mungkin tidak mengambil industri kita dengan cara mencuri. Mereka menjemputnya dengan kepastian, insentif, dan kecepatan. Jika Indonesia ingin bertahan di panggung global, maka respons kita tidak boleh lagi bersifat administratif. Ia harus strategis, politis, dan konkret.
Tarif mungkin tidak bisa kita hindari. Tetapi kehilangan industri adalah pilihan.